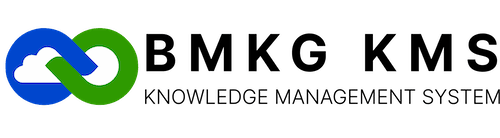Penulis: Yuliana Purwanti
Di tengah kecanggihan era digital, serta otomatisasi dan era kecerdasan buatan yang semakin marak, peran manusia dalam layanan publik seolah terpinggirkan. Namun jika jujur melihat sekeliling rasanya harus diakui bahwa yang dibutuhkan masyarakat saat ini justru layanan yang berakar pada rasa empati, penuh kreativitas dan inovatif. Tentunya hal-hal ini hanya bisa diberikan oleh manusia yang hadir sepenuhnya dengan hati, bukan sekadar menjalankan sistem. Perkembangan Revolusi Industri 5.0. menekankan kebutuhan mendesak pada kolaborasi antara manusia dan teknologi, dengan pendekatan yang tidak saja berpusat pada manusia, serta berbasis keberlanjutan, namun juga mendorong personalisasi layanan publik. Dibutuhkan gabungan kecerdasan buatan dan empati manusia untuk memberikan solusi yang lebih relevan dan berdampak sosial.
Tantangan bertambah karena di era VUCA ini perubahan terjadi begitu cepat bahkan tidak terduga, membuat hasil dan dampak kebijakan, terutama yang ditujukan untuk mengatur implementasi dan operasi layanan publik relatif sulit diprediksi. Pendekatan ala “business as usual” tidak lagi dapat menjawab berbagai masalah terutama yang saling berkaitan dan saling memengaruhi. Keberlimpahan data dan informasi yang tidak selalu jelas, terkadang jauh dari akurat, bahkan seringkali kontradiktif, membuat modalitas ini tidak bisa serta merta langsung dapat digunakan. Diperlukan analisis yang cermat dan pemilihan cara pandang yang tepat sebelum data dan informasi yang tersedia dapat digunakan sebagai landasan pikir.
Fenomena ini salah satunya dapat terlihat dalam bidang cuaca, iklim, kegempaan dan tsunami. Kejadian geohidrometeorologi yang semakin tidak menentu menimbulkan tantangan signifikan dalam analisis dan prediksi guna memenuhi kebutuhan layanan publik yang cepat dan akurat. Akses informasi yang semakin terbuka dan masyarakat yang semakin cerdas dan kritis, yang tidak saja menuntut transparansi dalam layanan namun juga memiliki kebutuhan untuk dilibatkan. Adanya kesenjangan sosial yang menjadikan kesenjangan akses pada layanan publik, berdampak pada timbulnya berbagai kelompok rentan dalam masyarakat.
Kombinasi berbagai hal tersebut secara signifikan telah menciptakan tekanan sekaligus peluang bagi munculnya berbagai inovasi. Berbagai studi dan pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa inovasi penghasil solusi terbaik adalah yang berakar pada rasa empati dan nilai sosial yang menjadi kebutuhan hakiki masyarakat yang dilayani. Dalam ketidakpastian dunia, socio-entrepreneurship menjadi gagasan segar dan menjanjikan untuk menjembatani kebutuhan ini. Berdasarkan studi yang dilakukannya di tahun 2019 Arundel mengemukakan gagasan perlunya sektor publik mengubah cara berpikirnya secara menyeluruh, terutama dalam memberikan layanan kepada masyarakat, dengan cara menggantikan pola pikir lama dengan cara pandang baru yang lebih terbuka terhadap perubahan. Dalam konteks sektor publik, tentunya hal ini termasuk para ASN sebagai pelaku layanan masyarakat, yang juga mendapat tuntutan untuk mengubah cara pandang dan cara kerjanya agar dapat melampaui hasil kerja konvensional. Saat ini, ASN tidak cukup menjadi pelaksana kebijakan namun diharapkan secara signifikan mengembangkan dirinya menjadi socio-entrepreneur, agen perubahan yang menggerakkan solusi yang inovatif, kolaboratif, serta membawa dampak sosial yang nyata.
Selaras dengan gagasan Arundel, Kamil, N.L.M pada tahun 2021 mengutarakan beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan Jacquemin & Janssen (2015; Wagner & Fain, 2018) dan menunjukkan bahwa perilaku kewirausahaan dalam sektor publik dapat meningkatkan kemampuan untuk mengatasi layanan publik yang belum optimal. Inisiatif untuk memperkuat dan menumbuhkan perilaku kewirausahaan di kalangan aparatur pemerintah menjadi sangat esensial dan potensial, karena pegawai negeri umumnya dikenal sebagai pihak yang cenderung enggan mengambil risiko dan menolak perubahan. Disinilah peran ASN menjadi sangat krusial, yaitu dengan memiliki semangat dan sikap kewirausahaan untuk meningkatkan efisiensi penyampaian layanan publik.
Sosio-entrepreneurship: Berfokus pada Inovasi, Berorientasi pada Misi Sosial
Socio-entrepreneurship didefinisikan oleh Forouharfar dkk. melalui publikasi riset di tahun 2018 sebagai sesuatu yang “berfokus pada inovasi yang berorientasi pada misi sosial, bertujuan menciptakan perubahan sosial yang transformatif melalui kreativitas dan pengenalan peluang sosial di berbagai sektor”. Irma dan Wu dkk menemukan bahwa sosio-entrepreneurship juga populer dengan istilah ‘social enterprise’ (SEV), ‘social entrepreneur’ (SE) and ‘social entrepreneurship’ (Sesh).
Dalam konteksnya di sektor publik, Bojan dkk (2025) mendefinisikan kewirausahaan sebagai “penggunaan perilaku dan praktik kewirausahaan untuk mendorong inovasi, perubahan, dan penciptaan nilai dalam organisasi publik, melalui upaya yang proaktif, penuh inisiatif, dan kolaboratif, sering kali dengan cara mengatasi hambatan hukum, regulasi, dan kelembagaan, demi meningkatkan hasil bagi masyarakat maupun organisasi”. Rowshan dan Forouharfar (2014) dalam Halim (2022) mengidentifikasi karakteristik kewirausahaan sosial yang paling sering disebutkan adalah menciptakan nilai sosial, inovasi, pencarian peluang, menciptakan perubahan sosial, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan menghasilkan dampak sosial.
Mengambil benang merah dari berbagai definisi para pakar dan praktisi tersebut, konsep socio-entrepreneurship sebetulnya sederhana yaitu menggunakan semangat kewirausahaan untuk menyelesaikan masalah sosial. Bukan tentang mencari keuntungan seperti halnya sektor swasta, tapi lebih fokus kepada penciptaan dampak. Dalam konteks ASN, ini berarti menjadi pegawai negeri yang memiliki empati, berani mencoba hal baru, dan fokus membantu masyarakat lewat ide-ide segar.
Dalam studi yang dilakukannya, Bojan dkk juga mengidentifikasi sebelas dimensi kewirausahaan sosial dari berbagai literatur. Sebelas dimensi tersebut daèat kita gambarkan implementasinya dalam konteks organisasi sektor publik sebagai berikut:

Gambar 1. Dimensi Kewirausahaan Sosial di Sektor Publik
Bagaimana penerapan Socio-entrepreneurship di BMKG?
Jika mencermati lebih dalam pada berbagai program di BMKG, sebelas dimensi tersebut sebetulnya sudah terlihat penerapannya, baik di sisi program substantif cuaca, iklim dan kegempaan maupun program administratif pendukung. Jika konsep socio-entrepreneurship ini dapat diterapkan secara holistik, tentunya nilai tambah dari program akan dapat diperbesar.
Untuk mempermudah pemahaman mari kita tinjau satu contoh dalam bidang pengembangan kapasitas, misalnya dalam pelatihan kepemimpinan. Dimensi pembaharuan (renewal) terpenuhi dengan jenis pelatihan yang berbasis aksi perubahan, yang menantang ketangguhan (resilience) ASN peserta pelatihan menjadi agent of change. Peserta menyusun rancangan aksi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, menggali inovasi (innovation) yang bisa dilahirkan, kemudian menjalankan aksi perubahannya. Hal ini tentunya membutuhkan daya inisiatif dan kecakapan (resourcefulness), keberanian menguji ide di lapangan dan mengambil risiko (risk taking) yang telah diperhitungkan, proaktif (proactive) dan kolaboratif (collaborative) dengan berbagai pemangku kepentingan untuk hasil terbaik. Peserta juga mengasah kepemimpinan (leadership), menguji kemampuan menyeimbangkan antara otonomi, visi dan kerahasiaan (autonomy, vision and secrecy) melalui pelaksanaan mandat organisasi dan kebebasan pemilihan metode dan pendekatan, juga melatih fleksibilitas (flexibility) dan adaptabilitas (adaptability). Satu dimensi lain yang masih besar potensinya untuk digarap adalah dengan mendorong berbagai peluang baru bagi inisiatif layanan, pendelatan program baru bahkan pengembangan unit jika diperlukan (new ventures). Selain memerlukan dukungan dan komitmen pimpinan, inisiatif semacam ini juga harus diberi wadah inkubasi untuk menguji sistem, proses, prosedur baru, termasuk penyediaan dua ruang alternatif yaitu: (1) ruang yang memadai untuk kegagalan dan (2) ruang pengembangan untuk mengintegrasikan ke sistem yang telah ada bagi inisiatif yang berhasil.
Bagaimana Knowledge Management menjadi penyangga dari berbagai dimensi Socio-entrepreneurship?
Dalam kerangka teori berbasis sumber daya (Resource-Based View Theory), pengetahuan adalah aset strategis yang bisa menjadi pembeda antar organisasi. Dalam pandangan konsep ini, sumber keunggulan kompetitif organisasi bukanlah semata-mata infrastruktur, teknologi dan fasilitas, atau anggaran besar, tapi sesungguhnya pengetahuan yang menjadi asset penting, terutama yang otentik dan sulit ditiru.
Sebagai satu pendekatan yang melibatkan aspek manusia, proses dan teknologi, Manajemen Pengetahuan atau Knowledge Management (KM) menjadi fondasi penting yang mendukung efektifitas dan keberlanjutan implementasi berbagai dimensi dalam socio-entrepreneurships dalam lingkungan organisasi, khususnya di BMKG. Selain memastikan pengetahuan dikelola baik, KM juga hadir sebagai alat untuk mengukur dan meningkatkan dampak sosial program, agar inisiatif sosial berhasil dan berkelanjutan. KM mengupayakan pengetahuan mengalir baik dari satu orang ke orang lain, dari satu kelompok ke kelompok lain, dari pengalaman praktik baik ke tindakan nyata.
Merujuk pada contoh penerapan socio-entrepreneurship pada program pelatihan kepemimpinan, dapat dibayangkan efisiensi dan efektifitas kegiatan jika di BMKG setiap pelajaran dari kegagalan program dan inisiatif, atau setiap keberhasilan inovasi kecil, atau setiap kesuksesan strategi komunikasi dapat didokumentasikan, dikemas, dibagikan dan diadaptasi oleh unit lain. KM yang baik mencegah hilangnya pengetahuan organisasi dan mempermudah replikasi praktik sukses, memudahkan ASN belajar dari pengalaman kolektif, tidak hanya mengandalkan intuisi dan inisiatif sendiri.
KM yang menjadi jembatan, tidak saja berperan menyimpan pengetahuan namun juga mengalirkan dan menghidupkan pengetahuan guna memperkuat sistem, proses, prosedur dan layanan serta memberi nilai tambah bagi BMKG sekaligus meningkatkan keunggulan kompetitif organisasi. KM mempercepat penyebaran inovasi dan pengambilan keputusan berbasis data, informasi valid dan bukti. Implementasi KM bukan sekadar pemenuhan tugas administratif tapi lebih tentang pengelolaan pengetahuan dan pengalaman. Di saat perbedaan antara inovasi dan imitasi semakin mengabur, dan modifikasi menjadi salah satu alternatif solusi, disinilah KM berperan signifikan yaitu dengan memberi akses ke pengalaman kegagalan sebagai pelajaran serta praktik-praktik sukses yang bisa diadaptasi.
Sebagai seorang socio-entrepreneur, ASN dituntut mampu mengelola pengetahuan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk menciptakan solusi sosial. Kamil merekomendasikan bahwa untuk mendorong perilaku socio-entrepreneurship, selain pelatihan yang berfokus pada kompetensi teknis, ASN juga perlu dibekali kemampuan untuk mengenali peluang, menambah nilai organisasi, dan beradaptasi dalam situasi kompleks. Socio-entrepreneurship tumbuh dari sensitivitas terhadap kebutuhan yang muncul secara mendesak di masyarakat. ASN berada di titik ideal untuk menghubungkan KM sebagai pengetahuan organisasi dengan kebutuhan nyata masyarakat, selanjutnya mengidentifikasi masalah sosial, lalu menggunakan pengetahuan dan jejaring untuk menciptakan solusi inovatif, diantaranya dengan melakukan imitasi dengan cerdas lalu menyesuaikan, memodifikasi dan mengadaptasi dengan kebutuhan lokal.
Lebih jauh, organisasi perlu menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan kolaboratif, memberi ASN ruang untuk berinovasi dan mengambil keputusan yang bermakna. Hal ini tidak hanya meningkatkan motivasi dan rasa kepemilikan, tetapi juga mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin baru dari dalam organisasi. Dalam konteks ini, KM berperan penting sebagai sistem pendukung agar ASN BMKG memiliki akses terhadap pengetahuan organisasi, belajar dari pengalaman, dan mengelola informasi untuk mengidentifikasi serta mengejar peluang yang relevan, juga untuk berinovasi dan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan dampak sosial. Saat kondisi krisis terjadi di BMKG, KM yang baik akan membantu mengingatkan bahwa krisis serupa pernah terjadi, dan organisasi pernah memiliki solusinya.
Bentuk nyata KM dapat berupa keberadaan forum diskusi lintas sektor atau lintas bidang sebagai ajang berbagi, dokumentasi berbagai kegagalan dan praktik baik di lapangan, penggunaan teknologi untuk berbagi ide dan solusi, ruang eksperimen untuk menguji ide dan keberanian mengambil keputusan. Untuk menjadi problem solver, ASN BMKG menggunakan pengetahuan dalam KM sebagai sumber inspirasi untuk berinovasi, menjadi agen perubahan dan menyelesaikan berbagai masalah masyarakat yang terkait bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika yang menjadi tanggung jawabnya. Keberadaan masalah tidak lagi terlihat sebagai hambatan namun akan dipandang sebagai potensi peluang bertumbuhnya individu dan organisasinya. Inovasi baru yang berdampak sosial akan lahir dari kombinasi kepedulian, kekuatan pengetahuan dan teknologi, untuk meningkatkan layanan BMKG sebagai dasar membuat berbagai keputusan akurat dalam berbagai sektor keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
REFERENSI
Arundel, A., Bloch, C., & Ferguson, B. (2019). Advancing innovation in the public sector: Aligning innovation mea- surement with policy goals. Research Policy, 48(3), 789–798. https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.12.001
B, P., K, P., V, S., Halim, N. A., Azmi, I. A. G., & P, J. (2022). Insights from global success stories of social entrepreneurship and review of social entrepreneurship transformation. SCMS Journal of Indian Management, 19(3), 20-33. Retrieved from https://www.proquest.com/scholarly-journals/insights-global-success-stories-social/docview/2735285285/se-2
Bojan, M. M., Cvjetkovic, M., & Masovic, J. (2025). Public sector entrepreneurship: Present state and research avenues for the future. Administrative Sciences, 15(3), 71. doi: https://doi.org/10.3390/admsci15030071
Forouharfar et al. (2018) Journal of Global Entrepreneurship Research 8:11 https://doi.org/ 10.1186/s40497-018-0098-2
Nurul Liyana Mohd Kamil, Christine Robert & Nur Hairani Abd Rahman (2021): Strengthening Civil Servants’ Entrepreneurial Behaviour: An Integrated Framework, International Journal of Public Administration, DOI: 10.1080/01900692.2021.1947317
Paramita Sofia, Irma (2015). T1- Konstruksi Model Kewirausahaan Sosial (Social Entrepreneurship) sebagai Gagasan Inovasi Sosial Bagi Pembangunan Perekonomian, Jurnal Widyakala, Vol 2. Tahun 2015. https://www.researchgate.net/publication/304392685_Konstruksi_Model_Kewirausahaan_Sosial_Social_Entrepreneurship_sebagai_Gagasan_Inovasi_Sosial_Bagi_Pembangunan_Perekonomian
Wu, Y. J., Wu, T. & Sharpe, J. (2020). Consensus on the definition of social entrepreneurship: a content analysis approach. Management Decision, ahead-of- print(ahead-of-print). doi: https://doi.org/10.1108/md-11-2016-0791