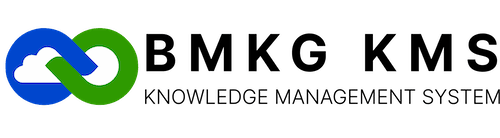Ika Nurmalasari
Di tengah dinamika tuntutan publik akan birokrasi yang tidak hanya bersih namun juga berdampak, peran Pejabat Fungsional Keuangan (PFK) mengalami pergeseran makna yang signifikan. Lebih dari sekadar penjaga buku besar anggaran negara, Pejabat Fungsional Keuangan kini berada di garda terdepan sebagai penjaga akuntabilitas sekaligus katalisator sosial yang beroperasi dalam semangat socioentrepreneurship. Transformasi ini menempatkan mereka sebagai elemen krusial dalam memastikan keuangan negara tidak hanya dipertanggungjawabkan secara prosedural, tetapi juga mampu menghasilkan dampak sosial yang nyata dan berkelanjutan.
Pejabat Fungsional Keuangan (PFK) tidak lagi cukup hanya “benar secara administrasi.” Mereka dituntut bermakna secara sosial. PPSDM MKG, sebagai lokus pengembangan kapasitas SDM BMKG, melihat urgensi membentuk profil PFK yang adaptif, strategis, dan berdampak. Ini bukan sekadar reformasi teknis, tapi reposisi peran: dari administrator anggaran menjadi agen perubahan sosial.
Secara fundamental, tugas utama Pejabat Fungsional Keuangan seperti Pranata Keuangan APBN/APBD dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah ialah memastikan setiap rupiah uang rakyat dibelanjakan, dikelola, dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel. Mereka adalah benteng pertama dalam pencegahan korupsi dan inefisiensi anggaran melalui serangkaian tugas teknis seperti verifikasi dokumen, pengujian tagihan, penerbitan perintah bayar, hingga penyusunan laporan keuangan. Peran ini adalah fondasi dari kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tanpa akuntabilitas keuangan yang kokoh, program-program pembangunan sehebat apa pun akan kehilangan legitimasi.
Secara regulatif, amanat ini ditopang oleh:
- PermenPANRB No. 45/2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN,
- PermenPANRB No. 24/2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan,
- serta penguatan integritas dan nilai ASN dalam PP No. 94/2021 tentang Disiplin PNS.
Namun, semangat zaman menuntut lebih. Konsep socioentrepreneurship, atau kewirausahaan sosial, yang berfokus pada penciptaan solusi inovatif untuk mengatasi masalah sosial dengan pendekatan bisnis yang berkelanjutan, kini merasuki sektor publik. Dalam konteks ini, Pejabat Fungsional Keuangan tidak lagi hanya berperan sebagai administrator yang pasif, melainkan sebagai seorang intrapreneur sosial di dalam birokrasi. Semangat socioentrepreneurship mendorong Pejabat Fungsional Keuangan untuk melihat melampaui angka dan prosedur. Mereka ditantang untuk menggeser paradigma dari sekadar “akuntabilitas prosedural” (memastikan semua aturan diikuti) menjadi “akuntabilitas dampak” (memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat).
Peran ini terwujud dalam beberapa aspek:
- Analisator Kritis Alokasi Anggaran: Dengan pemahaman mendalam tentang alur keuangan, seorang PFK yang berjiwa socioentrepreneur dapat memberikan analisis kritis terhadap efektivitas alokasi anggaran. Mereka dapat mempertanyakan, “Apakah alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan ini sudah tepat sasaran? Adakah model pembiayaan yang lebih efisien untuk mencapai hasil yang lebih baik?” Analisis ini menjadi input strategis bagi pimpinan untuk merancang program yang lebih berdampak.
- Inovator dalam Efisiensi: PFK dapat mengidentifikasi pos-pos anggaran yang tidak efisien atau rentan terhadap pemborosan. Berbekal data, mereka bisa mengusulkan realokasi anggaran ke program-program yang lebih inovatif dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Misalnya, mengusulkan pergeseran dari bantuan sosial yang bersifat konsumtif ke program pemberdayaan ekonomi produktif yang berkelanjutan.
- Pengawal Dana Sosial: Dalam setiap program yang memiliki tujuan sosial—baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan masyarakat Pejabat Fungsional Keuangan memastikan bahwa dana tersebut tidak hanya cair, tetapi sampai ke penerima manfaat dan digunakan sesuai peruntukannya. Dengan demikian, mereka secara langsung menjaga keberlangsungan dan keberhasilan inisiatif sosial pemerintah.
Menjadi Katalisator Perubahan Sosial Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pejabat Fungsional Keuangan juga mengemban fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam semangat socioentrepreneurship, peran ini diterjemahkan menjadi seorang katalisator sosial yang aktif.
- Menghubungkan Peluang: Dalam tugasnya, Pejabat Fungsional Keuangan sering berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan. Posisi ini memungkinkan mereka untuk menjadi penghubung. Sebagai contoh, ketika memverifikasi anggaran untuk program pelatihan UMKM, mereka bisa menghubungkan program tersebut dengan lembaga keuangan mikro atau platform digital untuk membantu pemasaran produk.
- Mendorong Transparansi Partisipatif: Seorang Pejabat Fungsional Keuangan modern dapat memanfaatkan teknologi untuk menyajikan data keuangan secara lebih mudah dipahami oleh publik. Dengan demikian, mereka tidak hanya melaporkan, tetapi juga mengedukasi dan membuka ruang bagi partisipasi publik dalam mengawasi anggaran. Transparansi ini adalah bahan bakar utama untuk membangun kepercayaan dan mendorong kolaborasi sosial.
- Menjadi Teladan Integritas: Di tengah upaya membangun ekosistem sosial yang lebih baik, integritas adalah mata uang yang paling berharga. Dengan menolak setiap upaya penyelewengan dan menjaga profesionalisme, PFK menjadi teladan dan menularkan budaya anti-korupsi. Sikap ini adalah fondasi krusial yang memungkinkan tumbuhnya inisiatif-inisiatif sosial yang sehat di tengah masyarakat.
Pada hakikatnya, Pejabat Fungsional Keuangan adalah titik temu antara regulasi dan realitas, antara angka dan dampak. Dengan memadukan ketelitian seorang akuntan, inovasi seorang wirausahawan, dan empati seorang pekerja sosial, PFK berevolusi menjadi agen perubahan yang strategis. Mereka tidak hanya memastikan negara tidak merugi secara finansial, tetapi juga secara aktif berkontribusi untuk memastikan setiap kebijakan dan alokasi anggaran membawa Indonesia lebih dekat pada cita-cita keadilan sosial.
Dari Akuntabilitas Prosedural ke Akuntabilitas Berdampak
PFK bertugas memastikan keuangan negara dikelola secara akuntabel—mulai dari verifikasi SPP/SPM, pengujian tagihan, hingga penyusunan laporan. Namun saat ini, mereka juga ditantang menjadi:
- Analis kebijakan anggaran sosial: Mengkritisi efektivitas alokasi program, seperti apakah anggaran pelatihan BMKG untuk masyarakat pesisir berdampak pada pengurangan kerentanan iklim?
- Inovator efisiensi: Menemukan pos anggaran yang tidak produktif dan merekomendasikan realokasi, misalnya, dari pengeluaran administratif ke edukasi literasi cuaca berbasis komunitas.
- Penjaga dana publik berdampak: Memastikan setiap rupiah untuk program inklusif—misal pelibatan perempuan dalam layanan iklim—sampai ke penerima manfaat.
PFK sebagai Katalis Sosial di Lingkungan BMKG
Di dalam ekosistem kerja BMKG, PFK berpotensi menjadi simpul penghubung antara teknokrat dan masyarakat:
- Menghubungkan pelatihan cuaca nelayan dengan skema pembiayaan mikro.
- Mengadvokasi keterbukaan informasi anggaran dalam bentuk dashboard publik.
- Menjadi wajah integritas di balik pencairan anggaran bencana, yang cepat, tepat, dan dapat dilacak.
Di PPSDM MKG, transformasi ini dimulai dari retooling mindset dan upskilling teknis. Pelatihan bagi PFK tidak lagi hanya soal regulasi keuangan, tetapi juga mencakup literasi sosial, pemanfaatan teknologi untuk transparansi, serta kemampuan komunikasi publik. PPSDM MKG menyiapkan mereka sebagai intrapreneur sosial dalam birokrasi, selaras dengan semangat BMKG untuk “perubahan yang berdampak.”
Pejabat Fungsional Keuangan bukan sekadar memastikan uang negara tidak hilang—mereka memastikan uang negara membawa pulang keadilan sosial.
Langkah-Langkah Strategis PPSDM MKG
- Pemetaan Kompetensi & Tantangan Lapangan
- Melakukan analisis kesenjangan kompetensi PFK saat ini vs peran yang diharapkan.
- Mengidentifikasi tantangan nyata yang dihadapi PFK BMKG di berbagai unit kerja (seperti lambatnya pencairan dana edukasi iklim, kesenjangan pemahaman anggaran publik, dll).
- Reformulasi Kurikulum Diklat Fungsional
- Mengintegrasikan materi socioentrepreneurship, manajemen perubahan, dan literasi dampak sosial dalam pelatihan PFK.
- Menambahkan studi kasus konkret BMKG: seperti pengelolaan dana pelatihan iklim berbasis komunitas, atau inovasi efisiensi dalam pengadaan alat meteorologi.
- Pelatihan Tematik & Proyek Intrapreneur
- Menyelenggarakan pelatihan tematik PFK berbasis tantangan nyata: “PFK sebagai Inovator Layanan Publik Keuangan.”
- Mengembangkan proyek intrapreneurship keuangan dalam pelatihan: peserta menyusun mini-inovasi keuangan berdampak di unit masing-masing.
- Kolaborasi Lintas Fungsi & Pengayaan Perspektif
- Mendorong pelatihan lintas jabatan (PFK dengan pranata humas, analis kebijakan, atau penyuluh cuaca).
- Menghadirkan narasumber dari sektor publik dan swasta (misalnya BPK, startup sosial keuangan) agar perspektif dampak lebih kuat.
- Pemanfaatan Teknologi & Inovasi Pembelajaran
- Menyediakan modul daring interaktif: “PFK dalam Ekosistem Inovasi Sosial BMKG.”
- Simulasi aplikasi akuntabilitas berbasis data: misalnya membuat dashboard real-time pemanfaatan anggaran kegiatan literasi cuaca.
- Mentoring & Showcase Praktik Baik
- Mengembangkan program mentoring dan coaching untuk PFK berprestasi sebagai role model.
- Mewadahi hasil-hasil praktik baik dalam galeri digital socioentrepreneurship ASN BMKG.
- Evaluasi Dampak & Tindak Lanjut
- Tidak hanya mengevaluasi dari aspek pengetahuan, tetapi juga dampak kinerja di lapangan (misalnya percepatan pencairan dana kegiatan edukatif, efisiensi pos belanja operasional).
- Menyusun policy brief dari temuan lapangan untuk pimpinan BMKG agar dapat digunakan sebagai dasar reformasi lebih luas.
Penutup
Dengan langkah-langkah ini, PPSDM MKG tidak hanya melatih keterampilan teknis PFK, tetapi juga menghidupkan semangat “keuangan untuk perubahan sosial” di lingkungan BMKG. PFK menjadi aktor penting untuk memastikan setiap rupiah negara tidak hanya terdata, tapi juga berdampak.
Referensi
PermenPANRB No. 45/2018 (Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN)
Definisi tugas PFK dan verifikasi keuangan, lihat Pasal 4–5, halaman 15–16 id.scribd.com+7peraturan.bpk.go.id+7peraturan.bpk.go.id+7.
PermenPANRB No. 24/2020 (Jabatan Fungsional Analis Keuangan)
Rincian fungsi analisis keuangan dan efektivitas anggaran, lihat Bab II, halaman 113–116 id.scribd.com+1id.scribd.com+1.
PP No. 94/2021 (Disiplin PNS)
Menekankan integritas dan akuntabilitas ASN sebagai dasar budaya kerja (konten tersedia di dokumen resmi, umumnya Bab I-II).
Permenkeu No. 181/PMK.05/2022 (Mekanisme Pelaksanaan Anggaran)
Menjabarkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran berbasis hasil (dapat ditemukan di Bab III-IV dalam PMK tersebut).
UU No. 5/2014 tentang ASN
Menegaskan kewajiban ASN untuk inovatif dan responsif (lihat Pasal 3 + 4, umumnya halaman 2–4).
OECD (2020), “Public Sector Innovation and Entrepreneurship”
Menjelaskan peran intrapreneur ASN sebagai katalisator inovasi—lihat halaman 25–28.
LAN RI (2021), “ASN Berkelas Dunia: Inovatif, Berintegritas & Berdampak”
Mendukung model socio-entrepreneurship dalam birokrasi; lihat Bab III, halaman 30–32 panduan.
Kementerian Keuangan RI (2023), Panduan Reformasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah
Menekankan prinsip value for money dan akuntabilitas sosial; lihat Bab II, halaman 45–49